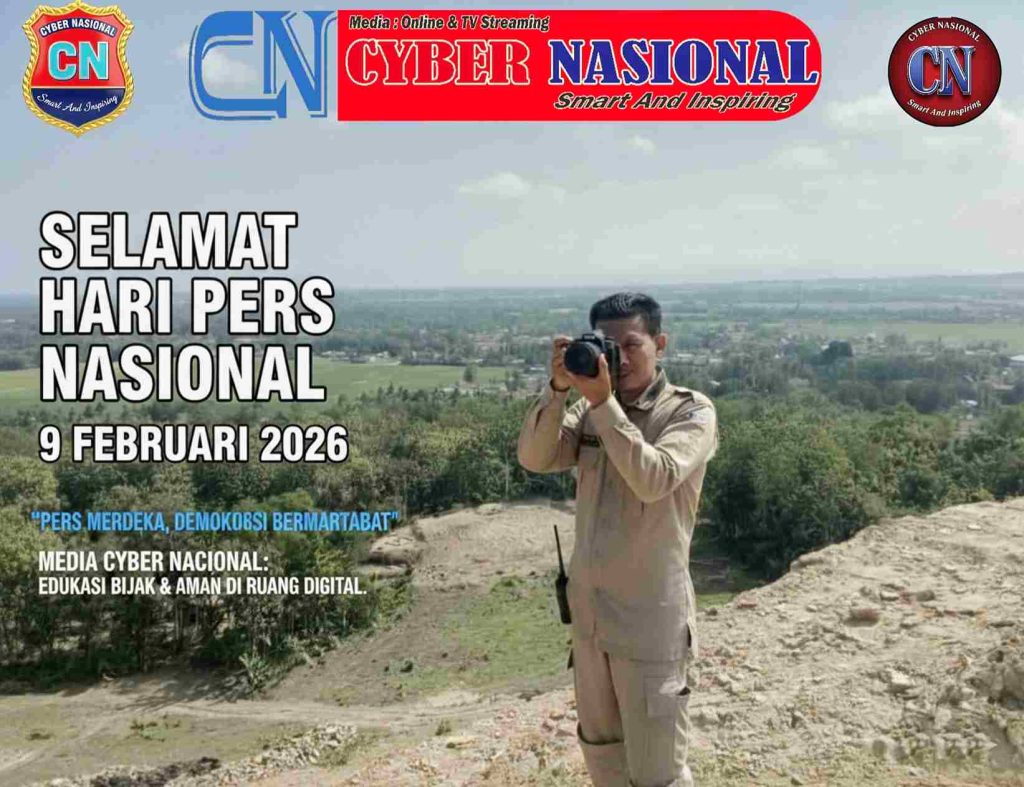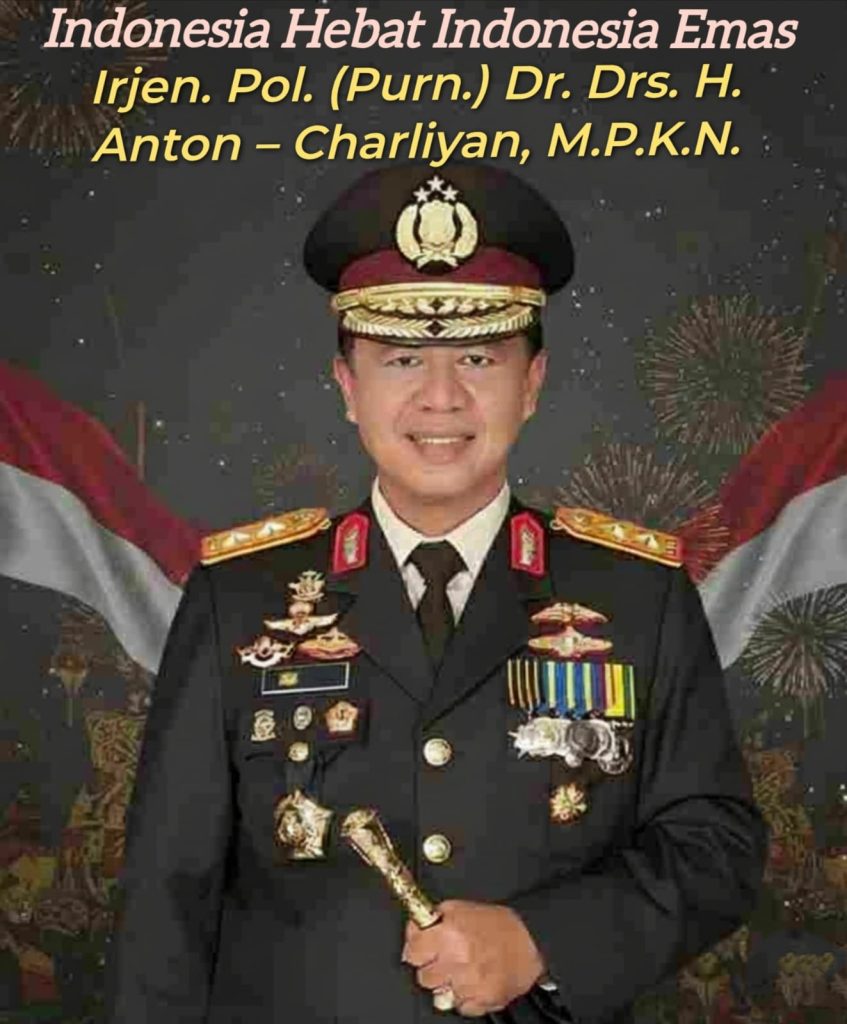TAPUNG HULU, RIAU — 10; Desember 2025- Di tengah pekik janji penegakan hukum yang berkeadilan, wajah keadilan di Kabupaten Kampar kembali tercoreng oleh praktik penegakan hukum yang dituding publik telah bertransformasi menjadi “budak korporasi”. Dua orang karyawan rendahan PT. ATS II (Arindo Tri Sejahtera), Darman Agus Gulo dan Herianto, kini terjerat jerat pidana layaknya kriminal kelas kakap hanya karena kedapatan mengambil brondolan sawit dengan total berat sekitar 80 kilogram, nilai kerugian yang ditaksir tak lebih dari Rp 400.000,00.
TAPUNG HULU, RIAU — 10; Desember 2025- Di tengah pekik janji penegakan hukum yang berkeadilan, wajah keadilan di Kabupaten Kampar kembali tercoreng oleh praktik penegakan hukum yang dituding publik telah bertransformasi menjadi “budak korporasi”. Dua orang karyawan rendahan PT. ATS II (Arindo Tri Sejahtera), Darman Agus Gulo dan Herianto, kini terjerat jerat pidana layaknya kriminal kelas kakap hanya karena kedapatan mengambil brondolan sawit dengan total berat sekitar 80 kilogram, nilai kerugian yang ditaksir tak lebih dari Rp 400.000,00.
Namun, bagi Penyidik Polsek Tapung Hulu, nilai kerugian yang setara harga sepasang ban motor bekas ini tak cukup untuk menggerakkan nurani. Mereka secara dingin menetapkan pekerja tersebut sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 372/374 KUHP tentang Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan. Penggunaan pasal berlapis yang lazim ditujukan untuk kasus kerugian besar atau berbasis jabatan ini memicu gelombang kecurigaan publik: Apakah ini diskresi hukum yang hilang akal, atau memang pasal pesanan dari pihak korporasi?
Respons PT. ATS II dalam kasus ini menjadi inti masalah yang paling menusuk. Pemerintah Desa Sumber Sari, Kepala Dusun V (Guna), perwakilan Camat Tapung Hulu (Sam), serta Pers Keadilan Tapung Hulu telah berulang kali berupaya memfasilitasi jalur Restorative Justice (RJ). Dua kali panggilan resmi mediasi dilayangkan melalui Polsek, termasuk pada hari ini, Rabu, 10 Desember 2025.
Namun, perusahaan perkebunan raksasa itu memilih sikap diam total, mangkir, dan tidak menunjukkan itikad baik maupun empati sama sekali.
Sikap apatis perusahaan ini sontak memunculkan pertanyaan kritis yang menggantung di benak masyarakat: Siapa sebenarnya pemegang kendali di wilayah hukum Tapung Hulu? Apakah Polsek tunduk pada hukum negara, atau pada kehendak korporasi? Apakah negara kini berfungsi sebagai alat penagih utang, bahkan alat intimidasi, bagi kepentingan modal?
Dalam sistem peradilan yang sehat, diskresi penyidik adalah ruang kemanusiaan untuk mempertimbangkan konteks sosial. Namun, dalam kasus Gulo dan Herianto, semua faktor kemanusiaan diabaikan:
– Nilai kerugian yang sangat kecil.
– Status pelaku sebagai pekerja rendahan dan warga setempat.
– Adanya tanggungan keluarga, termasuk bayi berusia 4 bulan.
– Permohonan maaf tertulis dan kesiapan keluarga menerima pemecatan tanpa pesangon.
– Permintaan solusi damai yang resmi dari pejabat desa dan kecamatan.
Semua permohonan yang dilandasi kepedulian sosial itu hanya dianggap angin lalu. “Jika penegakan hukum tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan manusia di balik kasus, maka yang bekerja di Polsek Tapung Hulu bukanlah instrumen keadilan, melainkan sebuah mesin tanpa hati,” kritik salah satu tokoh masyarakat setempat.
Istri tersangka mengungkapkan kesedihannya, “Kami hanya ingin hidup. Suami saya tulang punggung. Kami sudah memohon dan siap menerima suaminya dipecat tanpa pesangon. Mengapa kami harus disiksa begini?”
Kini, nasib seorang ayah, yang hanya mencari sisa-sisa rezeki di tanah korporasi, digantung pada keputusan yang lebih menyerupai balas dendam korporasi daripada tegaknya hukum yang proporsional.
Saat dikonfirmasi wartawan, Kapolsek Tapung Hulu, Iptu Riko Rizki Mazri SH MH, hanya memberikan jawaban yang sarat formalitas dan minim empati:
“Terima kasih banyak Bg.. Baik Bg… Segera kami berikan jawaban secara Resmi.. Untuk memberikan Kepastian Hukum”
Jawaban itu menuai sorotan tajam. Alih-alih memberikan pernyataan yang menyeimbangkan antara prosedur hukum dan rasa keadilan sosial, Kapolsek justru memilih diksi “Kepastian Hukum” yang dingin dan steril. Publik menilai respons ini menunjukkan hilangnya dimensi moral dan sosial seorang pemimpin institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan rakyat kecil.
Kasus brondolan sawit 80 kilogram ini jauh melampaui soal sawit. Ini adalah skandal etika penegakan hukum yang menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan bagi kaum papa di hadapan kekuatan modal.
Jurnalisme kritis mempertanyakan:
– Jika rakyat kecil dihukum maksimal karena mencuri 80 kilogram brondolan…
– Sementara ketika korporasi diduga mencuri tanah, ruang hidup, dan kesempatan masyarakat, mengapa negara dan aparat tiba-tiba menjadi bisu, buta, dan tuli?
Kasus ini adalah potret telanjang di mana keadilan dituding telah menjadi komoditas.
Yang sesungguhnya dicuri di Tapung Hulu bukanlah 80 kilogram sawit. Yang dicuri adalah keadilan, martabat, dan masa depan manusia kecil yang tak berdaya di hadapan arogansi korporasi dan ketajaman aparat yang salah sasaran.
(Tim Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.