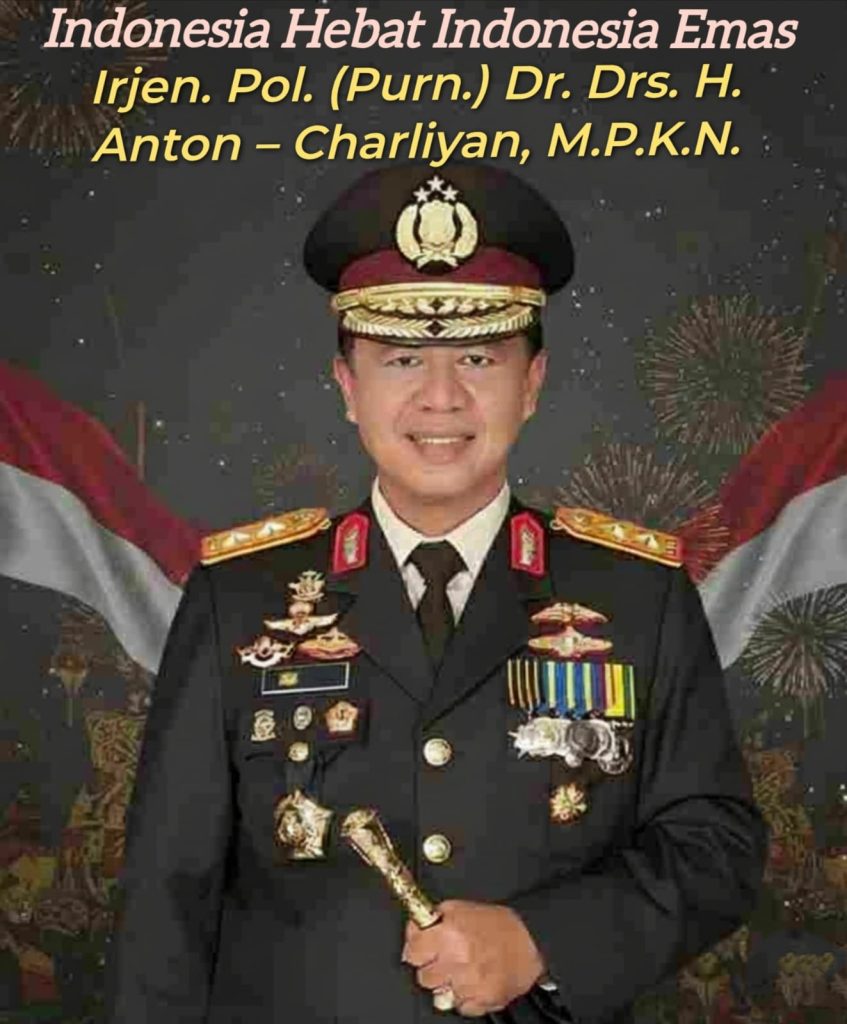Lamongan, 14 Oktober 2025– Sebuah pusaran konflik kepentingan di Lamongan telah mengungkap borok akut dalam tata kelola pemerintahan desa dan profesi jurnalisme. Peristiwa ini bukan sekadar perseteruan antarindividu, melainkan cermin keretakan etika ketika jabatan publik dan rompi pers dilebur menjadi satu alat tekan yang korosif, secara langsung mematikan independensi pers di tingkat akar rumput.
Titik didih konflik melibatkan Syaiful Anam (SA), Kepala Dusun Kauman Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, yang juga aktif menggunakan statusnya sebagai wartawan, melawan Ramlan (RM), anggota organisasi kemasyarakatan Shorenk Lamongan. SA melaporkan Ramlan ke Polres Lamongan atas tuduhan menghalangi tugas jurnalistik. Namun, di balik laporan ini, terkuak dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait rangkap profesi yang menjadi akar hilangnya independensi SA.
Pada Senin, 13 Oktober 2025, Ramlan memenuhi panggilan penyidik Unit IV Polres Lamongan. Didampingi oleh Ziwa, Ketua Dewan Pembina Shorenk Lamongan, pihak Ramlan segera menanggapi laporan tersebut dengan serangan balik yang terarah.
Ziwa, dalam keterangannya usai pemeriksaan, melontarkan kritik pedas, menyebut Lamongan kini berada dalam kondisi “Darurat Pers” bahkan lebih tepatnya “Darurat Moral”. Ia menegaskan bahwa laporan SA hanyalah upaya manipulatif untuk menyalahgunakan otoritas ganda.
“Seorang kepala dusun aktif, yang seharusnya melayani publik, malah menggunakan status wartawannya untuk melaporkan warga yang dianggap menghalangi kepentingannya. Ini bukan lagi Darurat Pers, ini perusakan sistemik terhadap independensi pers!” tegas Ziwa.
Shorenk secara terbuka mendesak Bupati Lamongan, Camat, dan Kepala Desa Tawangrejo untuk segera menjatuhkan sanksi administratif hingga pemberhentian kepada SA. Tindakan SA diklaim telah mencoreng marwah jurnalistik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah desa.
Investigasi mendalam menunjukkan bahwa praktik SA yang beroperasi dengan dua identitas—pejabat pemerintah di kantor desa dan “wartawan bebas” di lapangan—telah menciptakan iklim yang mematikan independensi jurnalisme lokal.
Sejumlah sumber anonim di kalangan jurnalis Lamongan menyebut SA kerap memanfaatkan status gandanya untuk menekan, mengarahkan, dan memiliterisasi liputan media lain. Penggunaan kekuasaan desa untuk menekan media lain agar tunduk adalah bukti nyata bahwa pena telah kehilangan kedaulatannya. Wartawan independen dipaksa untuk ‘nurut’ atau dihukum dengan pemutusan akses informasi desa.
Penggunaan profesi jurnalisme sebagai tameng atau senjata pribadi oleh pejabat publik merupakan penyakit kronis yang merusak kebebasan pers sejati. Ini adalah penghinaan terhadap etika pers yang mewajibkan independensi penuh dan tidak terafiliasi dengan kekuasaan.
Fokus kritik paling tajam tertuju pada status SA sebagai Kepala Dusun aktif yang merangkap profesi jurnalis, suatu kondisi yang melanggar dasar-dasar hukum tata pemerintahan desa. Independensi yang seharusnya menjadi mahkota profesi jurnalis telah ditukar dengan status jabatan publik.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 secara eksplisit melarang perangkat desa memiliki pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tugas pokok.
Profesi jurnalisme menuntut netralitas mutlak dan tidak boleh berada di bawah bayang-bayang kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, tindakan SA secara hukum terancam sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatannya sesuai Pasal 53 UU Desa.
Kasus SA vs Ramlan telah melampaui batas perselisihan personal. Ini adalah alarm keras bagi penegak hukum, Dewan Pers, dan pemerintah daerah. Ketika independensi jurnalisme dikorbankan demi kepentingan pribadi seorang pejabat, maka fungsi kontrol sosial pers pun lumpuh.
Laporan yang diajukan SA, meskipun dibungkus dalih “penghalangan kerja jurnalistik,” tampak sarat kepentingan politik dan upaya membungkam pihak yang mengkritik liputannya. Apabila aparat penegak hukum memproses laporan ini tanpa terlebih dahulu mengusut pelanggaran rangkap jabatan dan konflik kepentingan yang dilakukan SA, maka negara telah memberikan legitimasi pada penyalahgunaan wewenang.
“Pers bukan alat balas dendam, dan jabatan publik bukan rompi pelindung untuk kepentingan pribadi,” tutup Ziwa.
Lamongan hari ini mengajukan pertanyaan moral: Apakah kita akan membiarkan kekuasaan kecil mabuk peran, menggunakan media sebagai gada untuk menekan lawan, dan meracuni sumur informasi publik? Jika praktik “mafia informasi tingkat desa” ini dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya marwah jurnalis, melainkan fondasi moralitas pemerintahan yang berintegritas.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.